Sebagai objek, keberadaan anak didik hanya berhenti pada satuan nilai, data statistik, atau besaran nilai rupiah tertentu. Anak didik dianggap tak lebih dari komoditas dan obyek eksploitasi sekolah melalui berbagai macam pungutan atau program-program palsu.
Beragam isu pemberdayaan, inovasi
pembelajaran dan pencerahan pendidikan hanya menjadi wacana kosong tak berbobot
saat anak didik diposisikan sebagai objek. Kebijakan kurikulum yang tidak jelas
dan bersifat coba-coba turut menempatkan anak didik sebagai objek. Tak luput,
mereka juga menjadi objek kekerasan epistemologis bernuansa kepentingan kala
terjadi transfer nilai-nilai dan pengetahuan di sekolah.
Penempatan anak didik sebagai objek mewujud juga dalam proses pendidikan
di sekolah yang membatu menjadi institusi formal tanpa jiwa. Dimana didalamnya
terbangun relasi kekuasaan monologis guru terhadap murid, tanpa ada ruang-ruang
sela untuk meluaskan imajinasi, kreasi, inovasi, pikiran-pikiran kritis, dan
pengebirian perkembangan alami anak. Sekolah menjadi tempat pengasingan anak
terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan sosio-kultural sekitarnya. Tembok
sekolah begitu kuat menghalangi proses subyektifikasi yang diharapkan mampu
membawa angin segar pada masa depan kemanusiaan anak didik. Adakah masa depan
peradaban di sini?
Melihat Anak Didik Sebagai Subyek
Dalam dunia pendidikan, sekolah menempati posisi sentral. Sekolah menjadi
sebuah lingkungan dinamis tempat berlangsungnya proses pendidikan dan
pengajaran terhadap anak didik. Disinilah nilai-nilai, pengetahuan, dan
ketrampilan diteruskan kepada anak didik secara sistematis dan terencana.
Guru-guru menempatkan dirinya sebagai medium organik yang menjadi penterjemah
materi-materi abstrak dalam kurikulum dengan dunia kehidupan nyata anak didik.
Masa depan kemanusiaan anak didik menjadi orientasi utama pembelajaran di
sekolah. Anak didik menjadi individu yang dihargai haknya dan dianggap sebagai
manusia yang unik serta berkemampuan khusus. Anak didik menjadi dirinya sendiri
dan bukan menjadi jiplakan guru. Anak didik dipahamkan bahwa mereka adalah
sepenggal narasi dalam sebuah kisah sosial yang lebih besar. Intinya, anak
didik benar-benar dilihat sebagai subyek. Dalam situasi seperti ini, falsafah
pendidikan learning to know, learning to do, dan learning to be yang dicanangkan oleh UNESCO dapat mengejawantah.
Pandangan progresif mengenai sekolah, dalam kaitannya dengan anggapan
anak didik sebagai subyek, menempatkan lingkungan sekolah sebagai sebuah
masyarakat mini yang mencerminkan interaksi sosial yang sehat, saling
menghargai, toleran, partisipatif, humanis, dan demokratis. Tak heran jika
Hadari Nawawi (1989) jauh-jauh hari menyampaikan bahwa anak-anak yang bersekolah adalah
individu yang merupakan totalitas kepribadian yang dinamis, sehingga harus
diperlakukan sebagai subyek. Beranjak dari anggapan tersebut, Nawawi
menyarankan perlunya ditumbuhkan pendidikan kebersamaan (togetherness education)
di sekolah yang diselenggarakan guna meningkatkan kesediaan dan kemampuan
anak-anak memahami dan menyadari kehadiran orang lain yang mempunyai hak
sebagaimana dirinya, dimana setiap orang diperlakukan dan memperlakukan orang
lain sebagai subyek.
Dalam relasi subyek-subyek ini guru harus mempunyai kompetensi dalam
mendidik anak agar mereka bersedia saling menghargai dan saling menghormati tanpa
merasa diinjak-injak haknya sebagai manusia. Guru berkewajiban memelihara dan
membina hubungan manusiawi atau hubungan sosial yang efektif di kalangan
murid-muridnya sehingga kekerasan dan pelecehan terhadap anak didik bisa
dikurangi. Mata pelajaran yang ada disekolah harus dikemas sedemikian rupa
sehingga tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan yang kering akan nilai-nilai
kebersamaan dan akhirnya menumpuk menjadi sampah ingatan.
Paradigma pendidikan baru yang menempatkan anak sebagai subyek membuat cara
pandang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik mengalami pergeseran
revolusioner. Pandangan keliru dalam memaknai kesalahan anak didik rentan
memunculkan kekerasan dan pelecehan. Kesalahan mesti dilihat sebagai salah satu
bagian dari proses pembelajaran. Alih-alih menekan anak, guru harus mengajak
anak duduk bersama, menelusuri kesalahan secara mendalam, membantu anak
meletakkannya dalam kerangka yang benar, memberi tahu anak tentang pilihan dan
konsekwensi serta membantunya mengatasi persoalannya tersebut. Tindakan diatas
memang memakan proses, namun dalam
jangka panjang perlakuan seperti ini akan mematangkan kepribadian anak dalam
kehidupan sosial. Dalam sebuah sekolah yang dicirikan oleh suasana yang empatis,
demokratis, partisipatif dan humanis, kesalahan diletakkan dalam proporsi yang
sebenarnya dalam rangka, meminjam kalimat Driyarkara, “memanusiakan manusia
muda”.
Sebagai subyek, hak anak untuk memperoleh pendidikan harus dilihat dengan
pemandangan yang lebih luas. Pendidikan tidak sekedar pemenuhan hak anak untuk mengikuti pelajaran di sekolah
melainkan juga hak untuk turut serta
dalam kehidupan sosio-kultural, baik di dalam maupun di luar sekolah. Implikasi
pandangan tersebut berimbas pada
pemahaman bahwa pengajaran formal di sekolah bukan satu-satunya model
pembelajaran seperti yang selama ini dipahami. Anak-anak bisa dididik melalui
pekerjaan, melalui kegiatan-kegiatan sosial, melalui partisipasi dalam
kehidupan kultural, melalui tanggapan-tanggapan emosional, melalui hubungan antar
manusia, melalui perjalanan dan olah raga, serta media lain yang sekiranya
memungkinkan anak untuk melakukan proses pendidikan alternatif. Dengan demikian
pendidikan tidak semata-mata merupakan suatu operasi intelektual kognitif yang
berlangsung di dalam batas-batas tembok sekolah.
Sebagai subyek, hak anak untuk
memperoleh pengetahuan harus dilihat dengan kacamata baru. Anak didik diajarkan
untuk terbiasa membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri dalam suatu konteks
sosial. Konsep ini mendasari metode-metode aktif dalam mempelajari lingkungan
bagi anak didik. Implikasinya, anak-anak hanya sedikit menggunakan “bahan” dari
sumber-sumber luar anak yang merupakan produk kebijakan orang-orang dewasa dan
menggunakan semua materi yang dialami anak. Ini memungkinkan berkembangnya
kreativitas anak-anak dalam memikirkan fungsi-fungsi lain yang mungkin
dimunculkan dalam suatu hal atau
peristiwa di luar konteksnya yang biasa.
Perlakuan di atas memuat konsekwensi
bahwa anak didik harus dididik agar mampu untuk “mendidik dirinya sendiri” dan
bahwa anak didik harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan dan
perubahannya. Segala jenis informasi, ketrampilan, dan pengetahuan tidak hanya
mengandalkan dari sekolah, karena adakalanya sumber-sumber yang diberikan oleh
sekolah tidak mempunyai kelanjutan dan tidak berkaitan dengan pengetahuan yang
dijumpai di lingkungan anak. Pengetahuan dari sekolah adalah pengetahuan buatan
dari orang-orang dewasa yang justru membentuk lingkungan sekolah (sebagai
lingkungan buatan) menjadi asing bagi anak. Alih-alih berakar dari pengalaman
anak sendiri, pengetahuan yang asing ini
justru berasal dari pengalaman umat manusia yang telah
dirasionalisasikan selama berabad-abad.
Peran anak didik sebagai subyek
menempatkan sekolah sebagai sarana sosialisasi. Didalamnya anak diajari untuk
menjadi sebuah bagian dari keseluruhan yang lebih luas. Anak harus ditumbuhkan
kesadarannya bahwa ia adalah subyek dalam relasi antar subyek, sehingga anak
dapat menyadari posisi dan peran yang sesungguhnya. Bukan melalui serangkaian
pengetahuan orang dewasa, namun murni berasal dari pengetahuan yang dibangun
oleh anak sendiri. Anak-anak diarahkan untuk menjadi dirinya sendiri, anak
didik diarahkan untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki dan berbagai macam
kemungkinan untuk mengembangkannya. Upaya-upaya penyeragaman, indoktrinasi, dan
intimidasi harus dihindari jauh-jauh terutama jika tindakan tersebut dijadikan
sebagai alat pembenar upaya guru untuk “mendidik” anak.
Di masa depan, sekolah yang menempatkan anak didik sebagai subyek membuat
mereka menjadi individu yang lebih mengandalkan pada pra-karsa sendiri dalam
belajar dan membangun pengetahuan. Oleh sebab itu, tempat belajar akan lebih
tersebar dan proses belajar akan lebih bergantung pada kemampuan seseorang
bukan lagi sekedar tradisi. Bagaimanapun pembelajaran yang hanya didasarkan
pada tradisi (dalam hal ini meliputi tradisi pengetahuan yang didapat dari
sekolah) tidak akan memunculkan kemandirian dan inisiatif anak didik.
Jelas sudah bahwa melihat anak didik sebagai subyek adalah sebuah
keharusan. Agar generasi negeri ini tidak hanya menjadi obyek peradaban. Agar
generasi negeri ini mampu menjadi subyek
dalam memberi aksen dan warna pada sejarah peradaban manusia. Bagaimana, sebuah
tawaran yang menggiurkan bukan?©
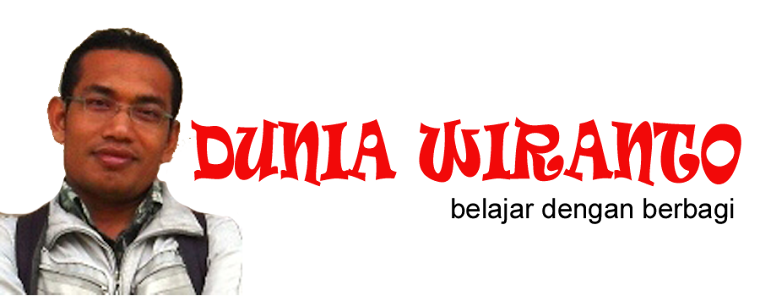

Tidak ada komentar:
Posting Komentar