Setiap tahun selama hampir 7 tahun penulis mengajar, tiap menjelang Ujian Nasional (UN) banyak teman-teman guru yang mengeluhkan bagaimana anak didik terlihat santai dan kurang “serius” dalam belajar, terutama untuk mata pelajaran yang kelak diujikan. Terkadang muncul seloroh kesal bahwa disekolah penulis, yang butuh lulus UN bukan murid tetapi gurunya.
Tak luput pula stempel “bodoh”, “malas”, “tidak bisa diatur” diberikan kepada mereka. Bahkan bagi beberapa guru yang mengalami tahap frustasi dengan santainya berkata, “biarkan saja mereka tidak lulus, toh mereka bukan anakku!”.
Kenyataannya,
sekolah tempat penulis mengajar terletak sekitar 65 kilometer dari ibukota
kabupaten. Tak ada sarana transportasi ke sekolah. Siswa yang mampu mengendarai
sepeda motor, yang berkekurangan mesti berjalan kaki. Sayangnya, lebih banyak
yang kurang mampu daripada mereka yang mampu. Kondisi jalan luar biasa parah,
kabar guru atau siswa terjatuh sudah lazim didengar.
Sebagian
besar siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah. Orang tua mereka juga
banyak yang pergi ke kota besar untuk mencari uang. Kasus siswi hamil di luar
nikah, hampir pasti terjadi tiap tahun sehingga menyebabkan mereka harus keluar
sekolah. Input siswa yang masuk memiliki kualitas yang rendah. Tak ada separuh
dari seluruh anak didik yang memiliki motivasi belajar. Mereka sekolah bukan
karena “ingin”, tetapi karena “harus”.
Jika
penulis mengaitkan antara harapan guru dengan kenyataan yang ada, tampak bahwa
siswa hanya dilihat sebagai objek. Meletakkan anak didik sebagai objek sama
artinya dengan tidak melihat mereka sebagai subyek yang mempunyai ke-diri-an.
Sebagai objek, keberadaan anak didik hanya berhenti pada satuan nilai UN, data statistik
kelulusan, atau besaran nilai rupiah tertentu.
Bagaimana
persoalan keluarga yang mereka hadapi, kemiskinan yang mereka derita, kurangnya
perhatian orang tua, menjadi isu yang tidak relevan dalam dunia persekolahan.
Sekolah menentukan kriteria untuk menormalisasi siswa dari kelakuan-kelakuan
yang “tidak normal”. Sedikit guru yang tahu dan “mau tahu” kondisi ke-diri-an
mereka.
Secara
umum, penempatan anak didik sebagai objek mewujud dalam proses pendidikan yang
membatu menjadi institusi formal tanpa jiwa. Didalamnya terbangun relasi
kekuasaan monologis guru terhadap anak didik. Mereka tak memiliki ruang publik
untuk melapangkan imajinasi, kreasi, inovasi, dan menyemaikan pikiran-pikiran
kritis. Sekolah menjadi lokus pengasingan anak terhadap dirinya sendiri dan
juga lingkungan sosio-kulturalnya. Kasihan anak-anak miskin, mereka bersekolah
dengan pengharapan akan adanya perubahan namun pada kenyataannya mereka justru
semakin “dimiskinkan”. Adakah masa depan kemanusiaan di sekolah seperti ini?
Guru “Baru”
Sebagai
subyek, anak didik menjadi individu yang dihargai haknya dan dianggap sebagai
manusia yang unik serta berkemampuan khusus. Anak didik menjadi dirinya sendiri
dan bukan menjadi jiplakan guru. Hadari Nawawi (1989) jauh-jauh hari mengingatkan
bahwa anak didik adalah individu dengan totalitas kepribadian yang dinamis,
sehingga harus diperlakukan sebagai subyek. Lantas guru “baru” seperti apa yang
dibutuhkan?
Pertama, guru
yang mampu mendidik dan memberi tauladan pada anak didik agar mereka saling
menghargai sebagai individu yang unik. Mata pelajaran dijadikan sebagai medium nilai-nilai
penghargaan dan tidak hanya menumpuk sebagai sampah ingatan.
Kedua, Guru
yang memiliki paradigma baru dalam memaknai kesalahan atau kegagalan anak
didik. Pandangan guru yang keliru dalam memaknai kesalahan anak didik rentan
memunculkan kekerasan, pelecehan, dan penghakiman. Alih-alih menekan anak, guru
harus mengajak anak duduk bersama, menelusuri kesalahan secara mendalam, membantu
anak meletakkannya dalam kerangka yang benar, memberi tahu anak tentang pilihan
dan konsekwensi serta membantunya mengatasi persoalan tersebut.
Ketiga,
Guru yang melihat proses pendidikan dengan cakrawala luas. Tidak hanya berpusat
di kelas, anak bisa dididik melalui pekerjaan, melalui kegiatan sosial, melalui
partisipasi dalam kehidupan kultural, melalui tanggapan-tanggapan emosional,
melalui hubungan antar manusia, melalui perjalanan dan olah raga, serta media
lain yang membantu proses subyektivikasi anak.
Keempat, Guru
yang sadar bahwa bukan mereka yang mendidik siswa, tetapi siswalah yang
“mendidik dirinya sendiri”. Pengetahuan sekolah adalah pengetahuan orang-orang
dewasa yang justru membentuk lingkungan sekolah (sebagai lingkungan buatan) menjadi
asing bagi anak. Implikasinya, guru seminimal mungkin menggunakan “bahan” dari
sumber-sumber luar dan menggunakan semua materi yang dialami anak. Ini akan mengembangkan
kreativitas anak didik dalam memikirkan fungsi-fungsi mereka sendiri di luar
konteks pengetahuan sekolah.
Akankah
nantinya Kurikulum 20013 memunculkan generasi yang gagap sejarah, gagu nilai,
gegar identitas, dan bungkam menyuarakan kebenaran? Jawabannya adalah ya, jika
guru masih memperlakukan anak didik sebagai obyek.
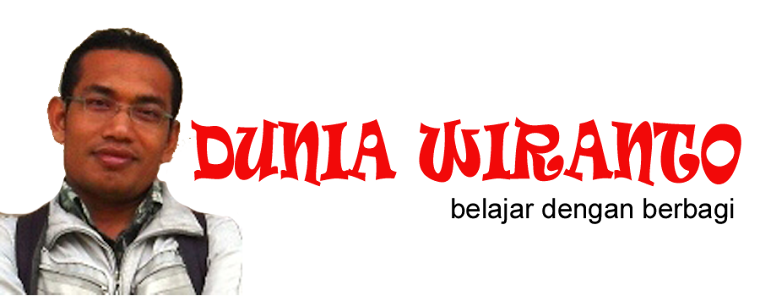

Tidak ada komentar:
Posting Komentar